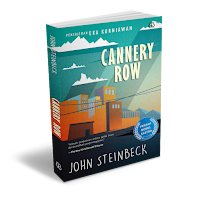Wednesday 19 December 2018
Resensiku; Catatan Seorang Backpacker di “Negeri Bollywood”
Judul Buku: Surga
Yang Lucu:
Petualangan Seru Menjelajahi Kashmir,
Himalaya, dan India
Pengarang: Yoli
Hemdi
Penerbit: Gramedia, Jakarta
Cetakan: 1, 2015
Tebal: x + 175 Halaman
ISBN: 978-602-03-1196-8
Apa yang akan terbersit dalam benak ketika
kita diminta membayangkan sebuah perjalanan berkunjung ke India? Barangkali hal
pertama yang muncul adalah bayangan tentang liburan, petualangan, keindahan
panorama Taj Mahal, atau bahkan kisah romantis sebagaimana tersaji dalam
film-film bollywood. Nyatanya, kata “perjalanan” tidak melulu berafiliasi
dengan wisata, tamasya, maupun setumpuk ide tentang liburan menyenangkan
lainnya. Lebih dari itu, sebuah perjalanan merupakan rangkaian episode yang
sarat dengan pembelajaran, emosi, kebahagiaan, hingga hal yang paling
memuakkan.
Buku ini berisi catatan perjalanan seorang
backpacker bernama Yoli Hemdi mengenai petualangannya menjelajahi anak benua India.
Melalui buku ini, ia tidak hanya berbagi kisah perjalanan wisata memotret
keindahan bumi Mahabharata, melainkan juga memuat episode seru yang sarat
dengan pelajaran bermakna. Ia menegaskan bahwa dalam sebuah kisah perjalanan, terdapat
muatan nilai yang mengajarkan keteguhan dan kedewasaan dalam melihat aneka
corak kehidupan.
Di dalam buku ini, beragam kejadian seru,
lucu, bahkan haru dikisahkan secara jujur dan apa adanya. Kisah tentang keindahan
dan keunikan India, hingga kejadian yang penuh paradoks tentang kebiasaan
maupun kondisi sosial masyarakat India, semuanya tertuang dalam penceritaan
Yoli Hemdi. Baginya, ragam kisah tersebut justru bermuara pada sebuah kesimpulan
India sebagai “surga yang lucu” (hlm. vi).
Siapa yang akan mengira eksotisme India
yang menyimpan berjuta keindahan, di mana Taj Mahal, Red Fort, Benteng Amber
maupun tempat-tempat istimewa lainnya berada, menyimpan sisi lain yang tidak
akan pernah kita duga bahkan dalam imajinasi teraneh sekalipun. Cerita berjudul
Toilet Terluas Sedunia misalnya, yang menuturkan kebiasaan primitif
kebanyakan masyarakat India yang masih suka kecing sembarangan.
Dalam cerita tersebut Hemdi menuturkan sisi
paradoks kebanyakan masyarakat India yang masih memiliki anggapan “boleh buang
air kecil di manapun mereka suka.” Sudah barang tentu, cara pandang tersebut
pada akhirnya membentuk kultur gemar buang air kecil di sembarang tempat bahkan
ketika tersedia toilet umum sekalipun. Dalam cerita ini pula, kita akan semakin
dibuat tercengang dengan jawaban seorang inspektur polisi kepada Hemdi ketika
menanyakan toilet. “Seluruh India ini toilet, Saudaraku! Pilih saja posisi yang
nyaman untukmu” (hlm. 25).
Masih tentang sisi paradoks masyarakat
India, Yoli Hemdi dalam Akting Pengemis Bak Artis, juga bercerita
tentang banyaknya masyarakat India yang “berprofesi” sebagai pengemis. Ia mengisahkan
pengalamannya berjumpa dengan seorang gadis kecil yang nekat mengemis ketika
berkunjung ke India Gate, kawasan wisata yang seharusnya steril
pengemis. Karena rasa iba, Hemdi pun memberikan lembaran 10 rupee kepada gadis
malang tersebut yang kontan saja tertawa girang.
Akan tetapi, alih-alih ikut merasa senang
karena telah berbagi dengan sesama, Hemdi justru menemukan kenyataan lucu
sekaligus haru sebab ternyata gadis kecil tersebut bukanlah seorang pengemis,
melainkan sesama pengunjung India Gate. Yang lebih mengejutkan, rupanya kedua
orang tua gadis tersebut berada tak jauh dari tempat Hemdi berada. Hebatnya
kedua orang tua gadis itu justru terlihat senang karena “akting” putri kecilnya
telah berhasil menaklukkan seseorang (hlm. 47).
Secara keseluruhan, meski ditulis dengan
gaya penuturan yang cenderung sarkastik dan apa adanya, rangkaian episode
petualangan dalam buku ini dapat dikatakan “seru”. Buku ini tidak saja menyajikan
cara pandang seorang backpacker dalam berpetualang, tetapi juga memuat banyak
pembelajaran hidup sesemisal tentang kelapangan dalam menerima kenyataan (Stupid
Mistake), maupun pelajaran tentang tidak baiknya perbuatan mencuri dalam
bentuk apapun itu (Mencuri Foto).
Selain itu, buku ini juga memberikan
catatan bermanfaat berupa saran bagi siapa saja yang ingin berkunjung ke bumi
Mahabharata, semisal tips mencari hotel murah, menghindari intrik pengemis, termasuk
juga tips untuk menghindari calo.
Tulisan ini pernah dipublikasikan di media online Portal Satu pada 04 April 2016
Posted by ibeng89 at 10:59 0 comments
Labels: gramedia, himalaya, india, kashmir, portal satu, resensi buku, taj mahal, traveling, travelling
Monday 17 December 2018
Resensiku; Latih Kemampuan Menulis Dengan Metode Free Writing
Judul Buku: Free
Writing:
Mengejar Kebahagiaan dengan Menuis
Penulis: Hernowo Hasim
Penerbit: B First (PT.
Bentang Pustaka)
Cetakan: 1, November 2017
Tebal: xl + 216 Halaman
ISBN: 978-602-426-088-0
“Menulis”
bagi sebagian besar orang identik dengan aktivitas yang menguras emosi serta
penuh dengan tekanan. Ini disebabkan karena untuk menulis, seseorang
membutuhkan konsentrasi penuh sehingga tidak jarang seseorang merasakan stress ketika
melakukannya. Ini pula yang kemudian menjadikan “menulis” dilabeli sebagai
pekerjaan “berat”, yang tidak semua orang dapat melakukannya. Menulis seakan
menjadi aktivitas menyeramkan bagi kebanyakan orang, bahkan bagi seorang
akademisi sekalipun.
Barangkali, alasan kenapa menulis terkesan
menjadi pekerjaan berat adalah karena tidak terbiasanya seseorang dalam
mengungkapkan gagasannya melalui tulisan. Selain itu mind set bahwa sebuah tulisan haruslah menggunakan
struktur kalimat, paragraf, serta gramatika yang baik semakin mempertegas image
“menulis” sebagai pekerjaan yang tidak mudah. Dapat dibayangkan betapa
kesulitannya seseorang yang tidak terbiasa menuangkan gagasannya dalam bentuk
tulisan, masih juga harus menuliskan gagasannya menggunakan struktur bahasa yang
sesuai standar. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mind set yang semacam
ini pada akhirnya akan membentuk mental “tidak siap menulis” atau bahkan trauma
menulis.
Memang tulisan yang baik, terlebih tulisan
akademis, adalah menggunakan struktur gramatika yang baik dan benar. Tulisan
semacam ini dapat dijumpai semisal di koran, jurnal, buku, dan sebagainya.
Namun demikian, yang perlu diperhatikan bahwa semua model tulisan tersebut
bertujuan untuk memahamkan atau memberikan informasi kepada orang lain. Dengan
kata lain tulisan-tulisan tersebut ditujukan sebagai konsumsi publik. Lantas
yang menjadi pertanyaan, apakah menulis memang hanya terbatas sebagai aktivitas
memproduksi tulisan sebagai konsumsi publik semata?
Hernowo Hasim dalam Free Writing
menyebutkan bahwa bisa saja tujuan sebuah tulisan dibuat adalah untuk
mengeluarkan “sampah” yang ada di dalam pikiran seseorang. Sebuah tulisan
diproduksi tidak selalu bertujuan agar dibaca oleh orang lain, melainkan juga
untuk diri sendiri. Hasim mengistilahkannya dengan MUDS atau menulis untuk diri
sendiri. MUDS merupakan aktivitas menulis yang tidak dikekang oleh peraturan
yang dibuat oleh individu, lembaga, atau pihak lainnya (hlm. 132). Dengan
demikian aktivitas menulis dapat terasa lebih ringan. MUDS menjadikan aktivitas
menulis menjadi lebih nyaman sebab dengannya seseorang dapat mengatasi
ketegangan saat menuliskan isi pikirannya.
Dalam hal ini Hasim menawarkan sebuah
metode latihan menulis yang diadopsinya dari Barat bernama free writing,
yakni menulis bebas (sebebas-bebasnya), tanpa harus terikat dengan aturan
apapun, termasuk aturan kebahasaan. Pendekatan kebahasaan di dalam free
writing sementara “dipinggirkan” terlebih dahulu. Karenanya, seseorang
dapat menuliskan apa saja yang diinginkan tanpa harus terjebak labih dahulu
dalam hal, semisal, penyusunan kata yang baik dan benar sesuai kaidah berbahasa.
Ini bertujuan agar (melatih) “si penulis” dapat benar-benar menuliskan secara
total dirinya (pikirannya) di atas kertas maupun gawai (hlm. xxvii).
Hasim mendasari gagasannya tentang free
writing dari tokoh-tokoh penggagas metode quantum learning/writing
seperti Roger Sperry, Lev Vigotsky, Bobbi Deporter, Mike Hernacki, Natalie
Goldberg, James W. Pennebeker, dan Peter
Elbow. Lev Vigotsky misalnya, mengistilahkan free writing sebagai
menulis dalam proses (hlm. 30). Dinamakan demikian sebab yang terpenting dalam latihan
free writing adalah proses menulisnya, bukan hasil yang ditulis.
Seseorang hanya perlu menuliskan apa saja yang terbersit di dalam pikirannya,
kemudian merasakan prosesnya –apakah merasa nyaman atau tertekan ketika menulis.
Sementara Natalie Goldberg, menggambarkan free writing sebagai menulis
tanpa bentuk. Seseorang hanya perlu mengalirkan kemudian menuliskan apa yang
ada di pikirannya, tidak lebih.
Menulis free writing terbilang mudah
dilakukan sebab ia memanfaatkan kinerja otak kanan untuk menulis. Merujuk pada
Sperry, otak kanan manusia bekerja secara acak dan emosional, sehingga ketika
diterapkan pada free writing, seseorang dapat menulis secara bebas dan spontan.
Dalam hal ini, yang perlu dilakukan dalam praktik menulis free writing
adalah konsisten menulis (bebas) secara berkala, dalam durasi 10 menit tanpa
berhenti. Dalam rentang 10 menit tersebut, kita hanya perlu menuliskan apa saja
tanpa perlu berpikir maupun melakukan koreksi terhadap yang dituliskan. Yang
terpenting adalah proses ketika menulis. Keep your hand moving!
Ini memberikan dampak positif berupa
terbentuknya mental siap menulis. Kesiapan mental dalam menulis penting bagi
seseorang untuk mengatasi ketegangan dan tekanan. Selain itu latihan menulis free
writing juga dapat mengondisikan kenyamanan (mental) ketika sedang menulis.
Dengan melakukan latihan free writing, sebagaimana disebutkan Haidar
Bagir dalam pengantar buku, seseorang dapat membangkitkan potensi serta
melejitkan kemampuan menulis. Selain itu, kehadiran free writing
berpeluang mengubah banyak orang yang tidak suka menulis atau trauma menulis
menjadi senang menulis.
Tulisan ini pernah dimuat di media online Liputan Kendal pada 19 April 2018.
Posted by ibeng89 at 13:47 0 comments
Labels: bentang pustaka, free writing, latih kemampuan menulis, menulis bebas, resensi buku
Friday 14 December 2018
Resensiku; Membaca Negeri Kabut dalam Perspektif Absurditas
Judul Buku: Negeri
Kabut
Penulis: Seno Gumira
Ajidarma
Penerbit: Grasindo, Jakarta
Cetakan: I, Oktober 2016
Tebal: IV + 159 Halaman
ISBN: 978-620-375-729-9
Absurditas merupakan istilah yang kerap kali
digunakan oleh para filsuf eksistensialis untuk menggambarkan betapa aneh dan
tidak masuk akalnya kehidupan ini. Salah satu di antara mereka adalah Albert
Camus, seorang filsuf sekaligus sastrawan kenamaan Prancis, yang berpendapat
bahwa hidup manusia di dunia ini adalah sebuah kesia-siaan. Manusia diciptakan
tanpa memiliki tujuan hidup. Karenanya, manusia senantiasa mencari esensi atau
tujuan dari penciptaannya. Namun demikian, pencarian tersebut pada akhirnya berujung
pada kesia-siaan.
Pemikiran Albert Camus ini tertuang dalam karya-karyanya,
salah satunya Le Mythe de Sisyphe. Di dalam buku tersebut, ketika
menjelaskan tentang absurdisme, Camus meminjam kisah mitologi Yunani, Sisifus,
seorang raja yang karena “pemberontakannya” kepada para dewa, kemudian dihukum
untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia, mendorong batu ke puncak gunung,
kemudian menggelindingkannya kembali kebawah, untuk selama-lamanya. Namun
demikian, meski ditakdirkan mendapat hukuman untuk melakukan pekerjaan sia-sia,
bagi Camus hukuman yang Sisifus jalani, sekaligus juga menjadi kemenangan atas
pemberontakannya kepada dewa.
Dalam hal ini, se-absurd apapun kehidupan
yang dijalani manusia, bentuk “pemberontakan” dengan terus menjalani kehidupan,
merupakan wujud kemenangan atas absurditas itu sendiri. Menjalani rutinitas
kehidupan –seperti apapun absurd dan sia-sianya– adalah bentuk perjuangan yang
mampu membuat seseorang bahagia, sebab dengan terus bergerak dan menjalani
kehidupan (yang penuh kesia-siaan), manusia dapat menemukan eksistensinya.
Dalam pada itu, tema absurditas nada-nadanya
juga digunakan oleh Seno Gumira Ajidarma “sebagai perspektif” dalam
cerpen-cerpennya yang terkumpul dalam buku Negeri Kabut. Betapa tidak,
hampir keseluruhan cerpen yang terdapat dalam buku tersebut menyiratkan
“kesia-siaan” sebuah perjalanan (hidup), yang meski demikian tetap harus dijalani
dan dinikmati. Cerpen-cerpen yang sarat dengan tema absurditas tersebar dalam
buku setebal 159 halaman itu. Mulai dari cerita seorang yang mengembara ke
seluruh penjuru bumi tanpa punya tujuan dan tanpa harus menemukan apapun, cerita
seorang pemain bola yang terus berlari menggiring bola mencari gawang terakhir
(di ujung dunia), hingga cerita pendekar
silat pilih tanding yang terus mengembara (tanpa tujuan) sambil menyeret-nyeret
peti mati berisikan mayat seorang wanita.
Sebut saja cerpen pembuka yang juga
berjudul Negeri Kabut misalnya, berkisah tentang seorang pengembara,
yang terus berjalan menjelajah ke seluruh penjuru bumi tanpa (harus) memiliki
tujuan. Dalam cerpen ini Seno menyisipkan kalimat “aku berpikir bahwa aku
memang ditakdirkan hanya harus berjalan, berjalan, dan berjalan, dan tidak
harus menemukan apapun” (hlm. 3). Kalimat tersebut secara tegas mempertontonkan
kepada pembaca perihal absurditas perjalanan (hidup) seorang pengembara
(manusia). Sebuah perjalanan adalah perpindahan dari satu persinggahan ke
persinggahan lain, termasuk dinamika hidup. Perjalanan hidup manusia senantiasa
bergerak dalam rutinitas serta fluktuasi pasang-surut dinamika kehidupan. Hanya
dengan terus menjalaninya-lah manusia dapat menemukan eksistensinya dan
mengalahkan absurditas itu sendiri, sebagaimana tergambar dalam kalimat “aku
hanya setia pada perjalanan itu sendiri” (hlm. 4).
Tema absurditas dalam buku Negeri Kabut
terasa semakin kental dengan adanya cerpen Di Tepi Sungai Parfum (hlm.
86), berkisah tentang perjalanan seorang anak manusia yang pergi meninggalkan
kampung halaman, melarikan diri dari semua persoalan, mengembara selama 3000
tahun lamanya, mencari negeri yang penuh kebahagiaan bernama dunia maya. Seno
mengakhiri cerpen tersebut dengan nuansa dramatis, yakni satu-satunya hal yang
diinginkannya (ketika tiba di tepi sungai parfum, jalan masuk menuju dunia
maya) adalah pulang ke kampung halaman, sekalipun memakan waktu 3000 tahun
perjalanan untuk pulang.
Dalam paham absurdisme, manusia kerap kali
merasa putus asa dan frustasi ketika berhadapan dengan rutinitas dan dinamika
kehidupan (absurdity). Karena itu, tidak sedikit manusia yang memilih
untuk lari darinya (dengan cara bunuh diri). Namun demikian, lari dari
absurditas bukanlah jawaban yang tepat sebab hal itu sekaligus menandai
hilangnya eksistensi dirinya. Manusia seharusnya menyadari absurditas dan hidup
berdampingan dengannya. Dengan cara itulah, manusia dapat memberontak terhadap
absurditas dan menemukan kebahagiaannya (eksistensi).
Selain mengusung ide absurditas sebagai
perspektif, nuansa realisme magis juga terasa begitu kuat dalam cerpen-cerpen
Seno di buku Negeri Kabut. Sebagai contoh dalam cerpen berjudul Sukab
Menggiring Bola, Seno secara terang-terangan membaurkan nuansa magis dengan
dimensi realis. Ini dapat pembaca temukan pada bagian di mana Sukab terus
berlari menggiring bola bahka ketika berada dipermukaan laut. Ia berlari
melibas segala, hingga laut pun ia jelajah. Berlari sambil sesekali mengoperkan
bola ke lumba-lumba (hlm. 59). Selain cerpen di atas, nuansa realisme magis
juga dapat pembaca temukan dalam cerpen Ratri dan Burung Bangau pada
bagian seribu burung bangau yang dengan paruhnya membawa bayi dalam gendongan,
untuk dihadiahkan kepada mereka yang merindukan kehadiran seorang anak.
Lebih lanjut, melalui buku ini, Seno seakan
mengusik serta mengajak pembaca untuk merenungkan kembali apa esensi serta
tujuan hidup manusia. Membaca cerpen-cerpen dalam buku setebal 159 halaman ini,
terasa sedang berdialog dengan begawan bijak yang menghapuskan “kebingungan”
yang tak jarang menjangkiti manusia modern dalam perjalanan mencari
eksistensinya. Seno telah memasang lampu
penerang agar pembaca tidak tersesat dalam absurditas.
Sudah semestinya Negeri Kabut menjadi
bacaan wajib baik bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang sastra maupun bagi
pecinta sastra secara umum. Seno sendiri dalam testimoninya mengatakan bahwa,
“Sebenarnya saya tidak pernah ingin menulis cerpen-cerpen seperti dalam Saksi
Mata –cerpen-cerpen itu dilahirkan oleh keadaan. Cerpen-cerpen yang selalu
ingin saya tulis, adalah seperti yang terkumpul dalam Negeri Kabut ini.”
*Tulisan ini pernah dimuat di Harian Bhirawa dengan judul Memahami Absurditas Perjalanan Kehidupan pada 09 November 2017
Akses juga laman Pelatihan Sdm di Jogja
Akses juga laman Pelatihan Sdm di Jogja
Posted by ibeng89 at 13:42 0 comments
Labels: absurditas, cerpen, gramedia, grasindo, karya sastra, negeri kabut, resensi buku, resensi sastra, sastra, seno gumira, seno gumira ajidarma
Thursday 13 December 2018
Resensiku; Potret Kehidupan Dalam Sebuah Karya Sastra
Judul Buku: Cannery
Row
Penulis: John Steinbeck
Penerjemah:
Eka Kurniawan
Penerbit: Bentang Pustaka, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Juli 2017
Tebal: viii + 236 Halaman
ISBN: 978-602-291-407-5
Sebuah karya sastra tak
jarang berperan sebagai refleksi atau pantulan dari situasi-kondisi manusia dan
masyarakat. Ia menjelma sebagai tiruan atau salinan dari kehidupan manusia. Mulai
dari tradisi, struktur sosial, nilai moral, sistem politik, hingga problematika
kehidupan yang terjadi di masyarakat, semuanya termuat dalam rangkaian besar
sebuah narasi sastra. Pada akhirnya, karya sastra tidak hanya menjadi sarana untuk
mengekspresikan keindahan semata, melainkan juga tentang humanitas, kebaikan,
hingga ketidakberdayaan dan ketertindasan, yang meski demikian tetap menyimpan
pendar cahaya harapan.
Seperti halnya dalam Cannery
Row, karya sastra gubahan John Steinbeck ini menyoroti segenap kehidupan
manusia, baik sebagai makhluk sosial maupun sebagai individu yang penuh dengan
“ketidakterdugaan.” Buku yang dalam edisi bahasa Indonesianya diterjemahkan
oleh Eka Kurniawan ini menjadi sebuah mimesis atas struktur sosial-kehidupan
masyarakat Cannery Row, Monterey California. Kisah-kisah tentang
kesetiakawanan, keterasingan, serta kedermawanan terangkum secara apik dengan
nuansa realis-imajinatif. Dengan menggunakan premis yang polos dan sederhana, Cannery
Row menyajikan kisah memukau tentang kemanusiaan.
Dalam buku ini diceritakan
bahwa Cannery Row, Monterey California adalah tempat bagi kerumunan manusia,
timbunan sampah, pabrik-pabrik pengalengan sarden, restoran, tempat pelacuran,
serta rumah-rumah kumuh berada. Penduduknya adalah para pelacur, germo, tukang
judi, dan anak-anak haram jadah (hlm.vi). Hanya ada kebisingan, kebusukan,
serta bau amis pabrik pengalengan sarden di Cannery Row. Di tempat itulah, Doc
yang seorang ahli maritim baik hati, Mack dan teman-temannya yang dianggap
sebagai sampah masyarakat, serta Lee Chong seorang pedagang Tionghoa yang
dermawan menetap.
Polemik dalam narasi buku
bermula dari keinginan Mack dan teman-temannya untuk mengadakan sebuah pesta
kejutan bagi Doc sebagai bentuk tindakan balas budi. Keinginan tersebut muncul sebab
hanya Doc satu-satunya orang di Cannery Row yang senantiasa memperlakukan
mereka dengan baik –meski pada kenyataannya Doc memang selalu baik kepada semua
orang. Kebanyakan penduduk Cannery Row menganggap Mack dan teman-temannya
sebagai sampah masyarakat, sehingga mereka dijauhi bahkan “ditolak”
keberadaannya. Jika pun ada yang mau berbaik hati, itu semata karena takut atau
tidak mau berlama-lama berurusan dengan mereka.
Namun apa boleh buat, rencana
Mack dan kawan-kawan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pesta kejutan
yang mereka persiapkan sebaliknya berubah menjadi kekacauan yang tak
terhindarkan. Sekelompok pelanggan dari Bear Flag tiba-tiba datang membuat kegaduhan
di kediaman Doc, yang berujung pada perkelahian. Karenanya, bukan pesta kejutan
yang menyambut, melainkan pecahan gelas, pecahan kaca jendela, serta piringan
hitam koleksi favoritnya yang hancur berserakan. Doc yang baru saja tiba justru
mendapati laboratorium tempat tinggalnya dalam keadaan kacau-balau dan
porak-poranda.
Akibat kejadian itu, Mack
dan gerombolannya secara sosial semakin terasing dan ditolak keberadannya.
Terlebih bagi Lee Chong yang dermawan, sebab ia merasa bahwa dirinyalah yang
membiayai kekacauan itu. Lee memberikan Mack dan teman-temannya modal untuk
mengadakan pesta dengan cara membeli kodok-kodok hasil tangkapan mereka. Bagi
warga Cannery Row, Doc terlalu baik untuk mendapat perlakuan semacam itu. Apa
yang telah Mack dan teman-temannya perbuat di kediaman Doc, semakin menegaskan
mereka sebagai pembuat masalah.
Yang menarik dari novel
ini adalah sisi humanitas yang terdapat dalam setiap bagian narasi novel. Ini dapat
pembaca temukan, misalnya, dari sikap yang ditunjukkan oleh tokoh Doc atas kekacauan
yang telah diperbuat Mack dan teman-temannya. Bagi masyarakat Cannery Row, niat
baik Mack untuk mengadakan pesta kejutan sepenuhnya telah dilupakan.
Sebaliknya, mereka percaya bahwa Mack dan teman-temannya telah membongkar paksa
dan masuk ke dalam laboratorium, mengacaukannya dengan kedengkian dan kejahatan
murni.
Namun tidak demikian
dengan Doc, meski menjadi pihak yang dirugikan, ia tetap menghargai niat baik Mack.
Baginya, kesalahan yang telah diperbuat Mack dan teman-temannya hanya bagian
dari kehidupan yang siapa saja dapat melakukannya. Sebaliknya, Mack dan
teman-teman, bagi Doc adalah representasi dari manusia yang merdeka. Mereka sekedar
melakukan apa yang mereka inginkan dan mereka percaya. Kekacauan yang mereka
perbuat bukanlah sesuatu yang tidak termaafkan. Pada akhirnya, masyarakat
Cannery Row akan menyadari hal itu dan merubah cara pandang mereka. Waktu akan
menyembuhkan segala sesuatu (hlm. 168).
Selain mengusung tema
kemanusiaan, kelebihan lain dari novel ini terletak pada kekuatannya dalam menghidupkan
suasana. Meminjam istilah Ignas Kleden, dalam novel ini “suasana”-lah yang
bercerita, tanpa bantuan pengarang dan tanpa bantuan cerita. Gambaran tentang suasana
pengap serta bisingnya Cannery Row, keindahan Carmel Valley yang dipenuhi
tanaman aster, rusa dan rubah yang sesekali muncul untuk minum di pinggiran
sungai Carmel, dilukiskan secara memukau dan terasa begitu hidup. Pembaca
seakan dibawa masuk dan mengalami sendiri hidup di Cannery Row.
Tulisan ini pernah dimuat dalam rubrik Pustaka, Harian Bhirawa pada 03 November 2017
Posted by ibeng89 at 13:49 0 comments
Labels: bentang pustaka, cannery row, john steinbeck, karya sastra, potret kehidupan, realis, resensi buku, sastra
Subscribe to:
Posts (Atom)